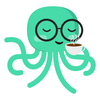Novel Back to Back by sweet-stripes

Novel Back to Back by sweet-stripes – “Jadi, kita sama-sama kembali ke masa lalu, Bar?”
“Kita sama, Sa. Sama-sama kembali ke sini.”
“Nggak mungkin! Nggak mungkin, Bar! Di dunia nyata mana ada alat buat kembali ke masa lalu? Hubungan kita nggak berubah walau kita kembali ke masa lalu. Kamu ngerti, kan?”
***
Setelah setahun bercerai, Prisa dan Bariq kembali bertemu di acara reuni kampus. Situasi canggung tidak dapat terelakkan. Bahkan sapaan sederhana sudah membuat mereka salah tingkah.
Hingga suatu ketika, secara misterius keduanya terbangun bersama di kamar yang dahulu mereka tempati ketika masih menikah. Prisa yang merasa dirugikan karena terlempar ke masa lalu, bersikeras mencoba segala cara untuk kembali. Sementara itu, Bariq justru mensyukuri kejadian di luar nalar yang menimpanya dan terus berdoa agar tetap berada di masa kini.
Lantas, akankah Prisa berhasil menemukan cara kembali ke masa depan atau malah terus terjebak di masa lalu seperti yang diharapkan Bariq?
Teaser Novel Back to Back
Benar-benar nyata.
Remasan jariku di pegangan tas berlapis kulit kian mengerat. Sejak berhasil melewati malam terakhir di sini, di rumah kami, aku bertekad tidak akan meneteskan air mata lagi. Setidaknya tidak di hadapan sosok pria yang sekarang tengah memasukkan koper terakhirku ke dalam bagasi mobil.
Punggung bidangnya sedikit membungkuk. Bisa kutebak, pasti dia tengah memeriksa isi bagasi untuk yang terakhir kali. Bariq selalu begitu. Selalu teliti dalam banyak hal, terkecuali dalam hal memahamiku.
Pria berambut pendek yang disisir rapi tanpa belahan, bergerak perlahan untuk memutar arah tubuhnya dan berhenti begitu menemukanku. Angin pagi tiba-tiba meniup dari sisi samping. Membuat ujung rambutnya yang sedikit ikal menutupi pandangannya. Bariq menyugar sekilas, tanpa melepaskanku dari radar.
“Tumben, pakai tas kecil.”
Tas? Oh, ini.
Mataku jadi tertuju ke arah objek yang dipertanyakan. Kemudian, aku tersenyum. Agak terharu karena dia menyadari bahwa pilihanku berbeda pagi ini.
“Perubahan kecil untuk memulai hidup baru,” jawabku dengan memaksakan senyum. Bariq mengangguk, dan ikut tersenyum.
“Hm ... sebenarnya nggak, sih,” aku kembali berkata. “Kata dokter, aku harus mengurangi beban di pundak. Makanya jadi ganti tas yang lebih kecil.”
Alis tebal Bariq terangkat seketika. Disusul oleh keningnya yang mengkerut. “Kamu sakit, Sa? Sakit apa? Kenapa nggak bilang sama aku?”
“Udah. Aku udah bilang. Mungkin kamu yang lupa.”
Aku masih berusaha tetap tersenyum untuknya ketika menyadari bahwa perasaan janggal ini terasa lagi. Pembicaraan ini terulang lagi. Dalam setahun terakhir sudah ratusan kali Bariq menanyakan hal yang sama.
Kenapa enggak bilang sama aku?
Dulu aku selalu memberitahunya mengenai apa pun. Tidak ada rahasia, karena bagiku dia satu-satunya tempat mengadu. Saat mendengar dia masih ingat pada hal-hal remeh dari ceritaku, rasanya luar biasa. Namun, suatu hari Bariq mendadak sering lupa. Aku sempat curiga dia mengidap tumor otak. Bahkan berpikiran mengajaknya ke dokter untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Hingga aku sadar kalau kekhawatiranku itu terlalu berlebihan. Bariq tidak sakit. Dia tidak melupakan jadwal tenisnya. Tidak pernah satu kali pun. Dia juga selalu mengingat sampai hal terkecil dan mampu menceritakan secara detail ketika aku tanya mengenai yang terjadi di lapangan. Hanya satu hal yang berubah. Posisiku di skala prioritas hidupnya.
Bariq menunduk selama beberapa detik, kemudian kembali mengangkat pandangan dan menatapku begitu lekat dari jarak puluhan sentimeter.
“Aku ... minta maaf, Sa.”
Kali ini dia tidak mencoba menjangkauku. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ketika dia menangisi keputusanku untuk berpisah, atau ketika memohon diberikan kesempatan sementara aku berdiri bergeming tanpa melemahkan argumen.
“It's okay. Aku udah maafin kamu, Bar. Aku yang lebih bersalah. Aku udah—”
“Nggak, Sa. Kamu nggak salah. Kamu berhak untuk hidup bahagia. Jangan merasa bersalah lagi. I'm okay now.”
Aku kembali mengulas sebuah senyum. Bariq pun melakukan yang sama. Perpisahan ini layak diakhiri dengan baik.
“So, jaga dirimu baik-baik.”
Aku mengulurkan tangan ke arahnya. Pria yang kini sudah berstatus sebagai mantan suamiku, ikut menjulurkan tangan dan meraih serta meremas tanganku. Dia terasa hangat, selalu hangat.
“Kamu juga. Salam buat Mama dan Papa, ya?”
Aku mengangguk kecil. Ingin sekali lagi menikmati rupanya untuk yang terakhir kali. Bagai cuplikan film pendek yang dipercepat, kenangan yang terjadi selama bertahun-tahun mengenalnya terputar jelas di ingatan.
Aku pernah sangat mencintainya. Bahkan masih hingga detik ini. Aku yakin Bariq juga merasakan yang sama. Sorot matanya tidak bisa berdusta. Nyatanya cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Butuh lebih dari sekadar cinta untuk menjaga keutuhan hubungan rumit itu.
Dan kini … aku sudah terbebas. Aku siap melebarkan sayap sejauh mungkin.
“Oke. Aku berangkat, ya. Takut keburu macet banget. Tol arah Bandung kalau Sabtu begini selalu padat merayap,” putusku.
Tautan tangan kami terlepas. Aku membenarkan posisi tali sling bag di pundak, kemudian mengeluarkan kunci mobil dari dalamnya. Sambil melambaikan tangan, aku berjalan menuju pintu pengemudi tanpa melihat ke belakang.
Begitu masuk ke dalam mobil, aku segera menekan tombol untuk menyalakan mesin, memasang sabuk pengaman, memeriksa spion luar juga dalam, lalu menurunkan kaca jendela untuk memberi salam perpisahan terakhir. Bariq sudah berdiri di samping mobilku. Dia membungkuk untuk menyamakan titik pandang kami. Sebelah tangannya mendarat di pintu mobil. Keempat jarinya yang menghadapku berhasil mencuri atensi. Dia juga menatapku, begitu dalam.
“Makasih banyak, Sa,” ucapnya dengan suara yang seperti tertahan di tenggorokan.
Aku hanya mampu menganggukkan kepala dan mengangkat kedua sudut bibir, sebelum memberitahunya lewat tatapan mata kalau kali ini aku benar-benar akan pergi.
Bariq melepas cengkeraman tangannya, lalu mundur selangkah. Sorot matanya tidak pernah bisa berbohong. Dia akan menangis sebentar lagi.
Maka dengan agak tergesa, aku memasukkan persneling dan menekan pedal gas secara perlahan. Mobilku mulai bergerak. Tanganku melambai sekali lagi ke arahnya. Dia membalas, matanya berkilauan diterpa sinar matahari pagi. Aku terus tersenyum tenang hingga pantulan sosoknya di kaca spion makin menjauh dan mengecil.
Saat bayangan pria itu sudah tidak terlihat, pertahananku pun runtuh seketika. Aku menangis dan terus menangis sampai tersengal. Cengkeraman kedua tangan di kemudi makin mengerat. Seolah inilah satu-satunya pegangan yang kupunya. Sementara dadaku berdenyut tanpa henti. Menekan-nekan hingga membuatku sulit menarik napas.
Hah ....
Ada apa denganku? Bukankah ini yang aku inginkan?
Ingat kata-kata Bariq, Prisa. Kamu harus bahagia.
Ya, aku harus bahagia.
Setiap berdiri sambil menatap seluruh hasil kerja kerasku yang dimulai sejak pagi hingga malam, rasanya fantastis. Seperti akhirnya bisa melahirkan setelah mengandung empat puluh minggu lamanya. Perumpamaan yang agak unik, bukan? Entah apa yang merasuki diriku hari ini. Padahal aku belum pernah mengalami hal itu. Pernikahanku berakhir sebelum sempat merasakan yang namanya hamil. Namun, kira-kira begitulah rasanya.
“Sebentar lagi selesai ya, Teh?”
Suara yang tiba-tiba muncul membuatku cukup terperanjat. Aku menoleh ke samping dan menemukan pemilik rumah tengah berdiri dengan ekspresi bahagia. Mata bulatnya berbinar, sementara kedua tangannya memegang paper bag berlogo putri duyung. Bisa kutebak, pasti isinya minuman dingin dan sebuah roti, atau mungkin cookies?
Konsumenku hari ini sangat royal. Waktu aku datang, dia menyuguhkan sepotong cheesecake dengan selai bluberi di atasnya, juga segelas es teh manis. Tadi siang, dia mampir lagi membawa satu paper bag kecil berisi cheeseburger, kentang goreng, juga kola. Sekarang ketika pekerjaanku hampir selesai, dia memberiku Starbucks.
Andai, setiap hari konsumenku sepertinya. Pasti aku bisa mengirit uang makan sampai jutaan rupiah.
“Iya, Teh. Tinggal dirapiin pinggirannya aja.” Aku melirik jam di dinding kamar bernuansa merah muda yang agak berantakan karena perabotannya dipaksa pindah semua ke sisi di belakangku, kemudian kembali melihat ke arah lawan bicara. “Saya usahakan sebelum jam delapan udah selesai. Sashanya nggak tidur di sini dulu kan, ya? Khawatir masih bau cat,” lanjutku.
Wanita muda berwajah ayu di hadapanku menyunggingkan senyum. Tangannya terulur, memintaku menerima pemberiannya. “Kalau itu aman. Sama ini. Diminum dulu, Teh. Biar semangat terus.”
“Wah, makasih banyak, ya. Padahal saya udah bilang nggak perlu kasih makanan begini, lho. Jadi ngerepotin,” ucapku sembari menerima paper bag dari tangannya.
“Nggak ngerepotin, kok. Justru saya yang makasih. Udah bikin kamar Sasha jadi cantik begini.” Dia maju selangkah dengan kepala sedikit menengadah. “Kalau udah hampir beres, kelihatan makin bagus, ya. Saya suka banget sama hasilnya. Apalagi Sasha. Pasti dia bakalan betah di kamar terus, deh. Mandangin gambar kuda poni kesukaannya,” lanjutnya terdengar sangat bahagia. Seolah-olah sambil membayangkan bagaimana wajah anak kesayangannya ketika melihat kamar ini nanti.
Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut tersenyum lebar. “Sama-sama, Teh. Syukurlah kalau suka sama hasilnya.”
Lukisan mural dinding yang kukerjakan hari ini adalah permintaan Sasha. Anak kecil berumur lima tahun, dan berambut ikal sebahu yang sangat menyukai kartun My Little Pony. Tadi siang dia sempat menemaniku menyantap makan siang sambil menceritakan nama-nama kelima karakter kuda poni yang kulukis.
Kalau tidak salah, ada Pinkie Pie, Rainbow Dash, Twilight Sparkle, Fluttershy, dan Rarity. Mereka sangat berwarna-warni. Mulai dari pink, ungu, kuning, biru, oranye, sedikit hijau dan juga merah. Aku sampai kesulitan meracik warna-warna catnya tadi malam. Belum lagi latar belakangnya, sebuah kastil berwarna putih es yang dikombinasikan dengan warna ungu gelap. Oh, dan jangan lupakan ornamen-ornamennya.
Jujur saja, sepertinya ini adalah lukisan terumit yang kukerjakan sejak membuka jasa mural dinding setahun lalu.
“Ya, udah. Saya tinggal dulu ya, Teh. Semangat!” seru Irma sebelum berlalu dari dalam kamar tanpa menutup pintu. Kedua jendela pun terbuka lebar. Menjadi jalan bagi angin malam kota Bandung untuk datang menyapa, juga menemaniku hingga selesai melukis dan pamit pulang.
Aku suka situasi ini.
Kaleng-kaleng cat beraneka warna tergeletak di lantai yang sudah dilapisi plastik cor meteran. Ada beberapa kuas dengan beragam ukuran yang kuletakkan di atas tutup kaleng cat. Juga selotip kertas berwarna kuning yang membantuku melindungi setiap sisi objek yang sudah dicat, sebelum mulai mengecat objek lainnya.
Tidak terasa sudah setahun aku terjun di bisnis penyedia jasa mural dinding khusus rumah. Dulu konsumenku belum seramai sekarang. Butuh waktu dua minggu tanpa henti memposting karya-karya yang kukerjakan di kamarku sendiri, juga di beberapa area dinding rumah orangtua, sebelum datangnya pesanan satu per satu.
Sebenarnya, hingga sekarang orangtuaku masih tidak mendukung keputusan untuk menyeriusi hobi melukis ini. Bahkan dulu aku sangat ingin masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain, tetapi mereka mendesakku untuk mengambil sekolah bisnis saja. Aku ingat benar apa kata Papa waktu itu.
“Zaman sekarang, apa-apa dibisnisin, Prisa. Mendingan kamu belajar bisnis dulu yang benar, baru melanjutkan hobi melukis. Kalau kamu kuliah seni, tapi nggak bisa bisnis, ujung-ujungnya cuma jadi pelukis jalanan. Kayak yang banyak dijual di pinggir jalan Braga.”
Saat itu, rasanya aku ingin sekali mendebat pendapat Papa yang bagiku sangat dangkal. Namun, yang kulakukan hanya mengangguk. Menurut, seperti yang selalu kulakukan. Sebab jika Papa sampai tahu kalau lukisan-lukisan yang dijual di sana kebanyakan bukanlah hasil seorang pelukis jebolan universitas atau sekolah seni, maka kujamin beliau akan semakin meremehkan hobiku ini.
Itu dulu. Tiga belas tahun yang lalu.
Sekarang zaman sudah makin berkembang. Pelukis bisa mengekspresikan diri lewat banyak media dan dapat menghasilkan banyak uang. Bagi yang jago menggunakan gadget, pasti memilih untuk melukis memakai perangkat lunak desain yang banyak dijual di pasaran. Sementara untuk yang lebih menyukai melukis langsung menggunakan cat dan kuas, tetap setia memakai media kanvas atau kertas untuk menuangkan ide-ide mereka. Dan aku masuk ke kategori yang kedua.
Aku suka ketika tanganku terkena cat. Aku suka ketika mengaduk campuran cat dan menemukan warna-warna baru, kemudian menyapukan kuas yang basah ke permukaan kertas atau kanvas. Aku suka melukis dan bisa menghabiskan waktu seharian tanpa bosan sama sekali.
Aku menyukai hobi ini, meski tidak ada yang benar-benar memberi dukungan. Termasuk, mantan suamiku yang entah bagaimana kabarnya sekarang.
Hah ... cukup dengan masa lalu. Sekarang aku harus segera menyelesaikan pekerjaan, supaya bisa cepat pulang dan merebahkan tubuh di atas kasur empuk. Istirahatku harus cukup. Besok masih ada pekerjaan mural di daerah Dago yang rencananya akan kukerjakan selama dua hari berturut-turut, sebelum bisa menarik napas sejenak di hari Minggu. Meski secinta itu pada melukis, tetap saja aku butuh hari libur.
Aku mengambil kuas terkecil, berniat mencelup ujungnya dengan cat berwarna kuning cerah. Namun, nada dering panjang yang berasal dari ponsel di dalam tas, membuatku segera meletakkan kuasnya lagi.
“Halo, Put. Ada ap—”
“Teteeehhhh ….” Suara nyaring yang memekakkan sontak membuatku menjauhkan ponsel dari telinga.
Selalu, deh. Ketenangan jiwaku pasti terombang-ambing saat berkomunikasi dengannya.
“Kenapa, Put? Jangan teriak gitu, atuh. Kalau telingaku kenapa-napa, gaji kamu dipotong buat bayar biaya dokter, ya!”
“Eh ... jangan dong, Teh. Puput cuma lagi terlalu bersemangat,” jawabnya masih heboh.
Aku menghela napas, lalu memutuskan untuk duduk sejenak. Mataku terpaku pada paper bag berisi minuman dan camilan yang masih belum kubuka sama sekali. Sungguh waktu yang tepat. Aku baru ingat kalau kehausan dan agak lapar sejak tadi.
“Semangat kenapa?”
“Guess what, Teh! Eh, nggak usah pakai nebak, deh. Jadi ya, Teh. Teh Prisa udah fix di-booking sampai akhir bulan. Schedule penuh, Teh! Barusan ada yang booking buat empat hari! Tapi, tenang ... dibagi jadi dua hari dua hari, kok.
“Puput nggak setega itu bikin bos tercinta kerja rodi seminggu penuh. Lokasi rumahnya kebetulan deket dari rumah Teteh. Jadi Puput jamin nggak bakal capek di jalan. Oke, Teh?”
Selama mendengar celotehan berisi berita bagus dari Puput alias admin media sosial yang merangkap jadi asisten buat mengatur jadwal kerjaku, tangan kanan yang tidak punya tugas berat selain mengambil iced latte dan cinnamon roll secara bergantian, kini meraih tablet berukuran 10 inci dari dalam tas. Aku mengelap permukaan tangan ke celana sebelum membuka kunci layar, lalu mengetuk ikon folder berkas berjudul ‘Desain minggu pertama Mei 2023’.
Enam buah gambar dengan tema berbeda muncul memenuhi layar. Empat teratas sudah aku kerjakan. Tinggal dua gambar lagi yang belum. Untung saja gambar pilihan pelanggan esok tidak terlalu rumit. Dominan warnanya kecokelatan, putih, hijau serta abu dan hitam yang mengisi bentuk dedaunan, lingkaran, juga garis-garis yang disusun menyerupai lengkungan. Bisa kutebak, pasti pelangganku adalah pasangan muda yang sedang terbawa tren hunian kekinian. Serba estetis dan instagramable.
“Teh? Teh Prisa!”
Eh, ya ampun. Aku malah melamun. “Maaf, Put. Teteh lagi meriksa desain buat besok.”
“Teh Prisa mah kebiasaan. Kalau Puput cerita tuh, suka di-skip.”
Habis kamu berisik banget sih, Put. Aku pusing dengarnya.
“Tapi Teteh dengar yang bagian schedule bulan ini udah penuh, kan?”
Aku mengangguk, padahal Puput tidak akan melihat. “Dengar kok, Put. Tenang, Teteh udah bersyukur dalam hati. Nggak perlu diingetin,” jawabku menepis kebiasaannya yang selalu mengingatkanku untuk bersyukur setiap kali datangnya pesanan.
Puput ini adik sepupuku. Dia baru lulus SMA beberapa bulan lalu, dan langsung menodongku untuk memberinya pekerjaan sembari menunggu waktu tes masuk perguruan tinggi yang dia inginkan.
“Oke atuh. Nanti jangan lupa foto sama videoin mural hari ini ya, Teh. Biar malam ini juga Puput edit di Canva terus upload ke Instagram,” celotehnya masih berapi-api. Penyebabnya jelas. Bonus penjualan di akhir bulan.
Aku berdeham pendek. “Iya, iya. Udah dulu, ya. Dah.”
Dengan satu kali menekan layar, panggilan pun terputus. Aku mengembuskan napas panjang sambil meletakkan ponsel di atas tas, kemudian meregangkan tangan seraya memutar kepala beberapa kali. Bunyi retak pun bersahutan. Membuatku kembali menarik napas sedalam samudera sambil memejamkan mata, sebelum bangkit dan melanjutkan pekerjaan.
Okay. Sedikit lagi selesai. Mari lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Semangat!
Sebelum benar-benar bangkit, aku iseng memeriksa ponsel. Ada notifikasi email dari grup alumni fakultas, yang entah berisi apa. Juga satu pesan dari Tari, teman kuliah yang masih sesekali bertukar kabar denganku sampai sekarang.
Aku membuka pesan dari Tari lebih dulu. Dia menanyakan apakah aku akan datang ke Reuni Akbar kampus yang akan diadakan dua minggu dari sekarang. Pertanyaannya membuat keningku mengernyit.
Oh, mungkin itu isi dari email yang tadi aku acuhkan.
Aku segera memeriksa, dan ternyata benar. Email tadi berisi undangan untuk menghadiri Reuni Akbar 40 tahun kampusku yang akan diadakan akhir bulan ini. Membacanya membuat semangatku tersulut.
Ini adalah kesempatan emas untuk mengiklankan bisnisku. Memang dua bulan terakhir jadwalku selalu penuh, tetapi aku ingin lebih. Aku ingin setiap bulannya penuh, dan kalau itu tercapai aku ingin merekrut satu muralis untuk membantuku mengerjakan setiap pesanan.
Ide bagus! Lagi pula, Bariq tidak mungkin datang. Dari dulu dia selalu absen menghadiri reuni walau diajak teman-teman dekatnya. Berarti aman.
Baiklah. Malam ini juga aku harus mulai membenahi situs web portofolio yang sudah lama tidak kujamah, saking sibuknya mencari uang.
Segera setelah memantapkan hati, aku melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Berkutat dengan kuas terkecil, juga beraneka warna cat di dalam kaleng. Hingga lama-kelamaan, keringat memenuhi seluruh permukaan wajahku. Bagian menyempurnakan memang selalu membuatku lebih banyak berkeringat, jika dibandingkan dengan bagian menggambar sketsa dan awal mengecat. Mungkin karena bagian ini adalah bagian terpenting dalam membuat sebuah karya. Apa pun itu.
Meski dalam kondisi berkonsentrasi penuh, nyatanya memikirkan akan bertemu dengan teman-teman seumuran tetap mendatangkan gejolak aneh di dada. Aku gugup. Entah karena terlalu bersemangat atau karena sadar akan berada di situasi yang memaksaku terus bersandiwara.
Bulu kudukku meremang tanpa alasan. Aku berkilah, pasti ini terjadi karena angin yang baru saja bertiup kencang. Suhu Kota Bandung di malam hari selalu rendah.
Namun, kalau benar itu alasannya, mengapa aku terus membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja?
Daftar Isi Novel Back to Back
Bab 2
Bab 3
Bab 4
Tertarik baca kelanjutan cerita novel Back to Back? Segera install aplikasi Cabaca untuk baca novel online lebih privat dan nyaman. Cobain sensasi baca novel romantis atau novel genre lainnya mulai dari Rp5 ribu saja. Jangan download novel bajakan untuk tetap dukung penulis Indonesia menghasilkan novel berkualitas.